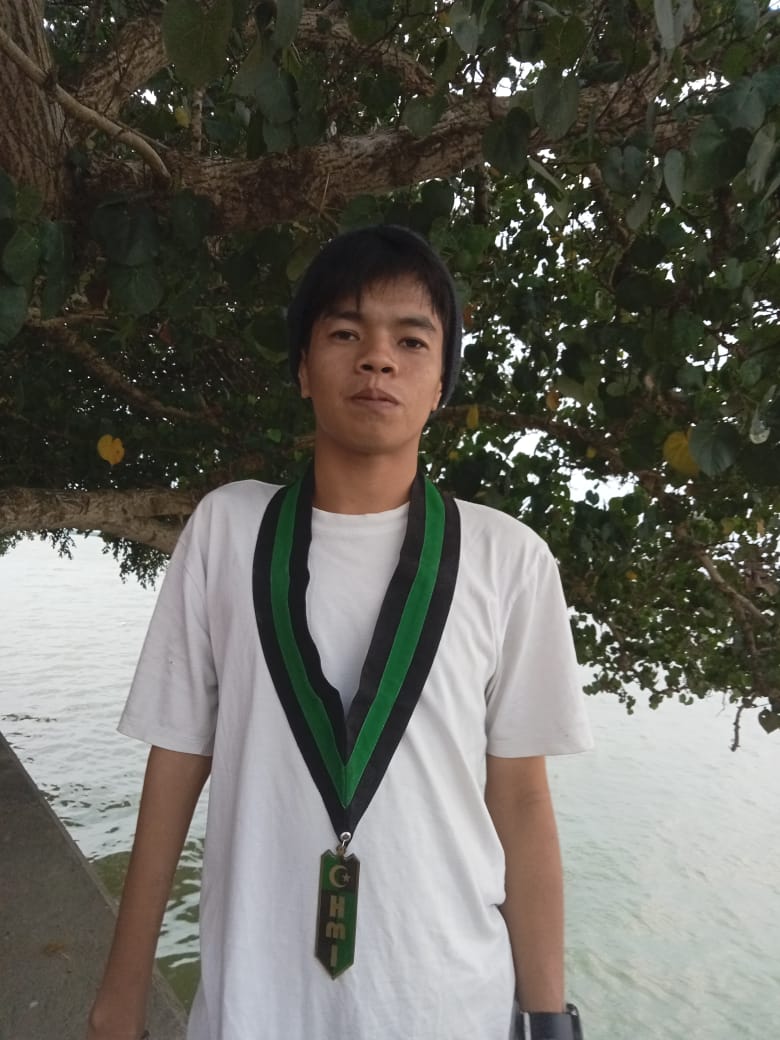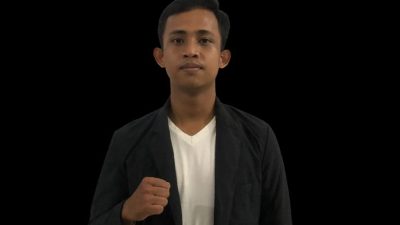Oleh:
Nasmaul Hamdani
MEDAN|PERS.NEWS – Indonesia kini tengah melangkah di jalur sejarah yang menentukan: fase bonus demografi. Pada periode 2025–2045, jumlah penduduk usia produktif akan mendominasi komposisi bangsa. Inilah momen langka yang hanya datang sekali dalam perjalanan sebuah negara. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi akan menjadi batu loncatan menuju Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Namun, bila gagal mengelolanya, ia justru berubah menjadi bencana demografi: ledakan pengangguran, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan stagnasi ekonomi.
Dalam lanskap perubahan besar itu, mahasiswa memegang posisi strategis. Mereka adalah generasi intelektual muda yang diharapkan menjadi motor peradaban, penyalur gagasan, sekaligus penggerak solusi. Namun, realitas menunjukkan bahwa sebagian dari kalangan mahasiswa kini tengah menghadapi tantangan baru-bukan hanya kemiskinan struktural atau akses pendidikan, melainkan arogansi intelektual.
Arogansi Intelektual di Era Bonus Demografi bukan sekadar kesombongan akademik. Ia lebih halus, namun berbahaya. Ia muncul ketika mahasiswa merasa cukup dengan teori, nilai akademik, atau sertifikat prestasi, tanpa mau turun langsung memahami kompleksitas masyarakat. Ia hadir ketika diskusi kampus hanya berhenti di ruang seminar, tanpa menjelma menjadi aksi nyata di tengah rakyat.
Mahasiswa yang arogan secara intelektual sering kali memandang dirinya sebagai “pemilik kebenaran” dan masyarakat sebagai objek yang harus diajari. Padahal, ilmu pengetahuan sejati justru lahir dari kerendahan hati untuk terus belajar dari kenyataan sosial. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan: semakin berisi, padi semakin merunduk.
Fenomena ini semakin nyata di tengah arus digitalisasi dan kompetisi akademik yang kian tinggi. Banyak mahasiswa berlomba-lomba mengumpulkan achievement, mengejar pengakuan, atau menampilkan kecerdasan di media sosial, tetapi lupa mengasah empati dan karakter. Akibatnya, intelektualitas yang seharusnya menjadi kekuatan transformasi justru berubah menjadi dinding pemisah antara “kaum terdidik” dan masyarakat umum.
Padahal, yang dibutuhkan bangsa di era bonus demografi bukan hanya orang pandai, tetapi orang cerdas yang berjiwa sosial. Intelektualitas sejati bukanlah kemampuan untuk menghafal teori, melainkan kapasitas untuk mengolah ilmu menjadi solusi yang membumi.
Mahasiswa harus menjadi jembatan antara kampus dan masyarakat. Pengetahuan yang mereka miliki seharusnya menjadi alat pemberdayaan, bukan pembeda status sosial. Misalnya, mahasiswa pertanian bisa membantu petani mengoptimalkan hasil panen dengan teknologi sederhana; mahasiswa teknik bisa merancang alat efisien bagi pelaku industri rumah tangga; mahasiswa ekonomi bisa mengajari pengelolaan keuangan mikro di desa. Itulah bentuk nyata dari intelektualitas yang membumi.
Lebih dari itu, mahasiswa juga harus memahami bahwa bonus demografi bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga ujian moral. Di tengah dunia yang semakin pragmatis, mereka dituntut untuk menjadi penjaga nilai: kejujuran, keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab. Jika kecerdasan tidak diimbangi dengan moralitas, maka intelektualitas akan kehilangan arah.
Risiko Jika Intelektualitas Menjadi Hambatan
Jika mahasiswa gagal menundukkan arogansi intelektual, dampaknya serius bagi masa depan bangsa. Pertama, akan terjadi kesenjangan antara dunia akademik dan realitas sosial. Lulusan perguruan tinggi banyak, tetapi sedikit yang benar-benar siap bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Akibatnya, angka pengangguran intelektual meningkat.
Kedua, muncul elitisme baru di kalangan terdidik. Mereka lebih sibuk memperdebatkan konsep daripada mengatasi persoalan riil di masyarakat. Hal ini bisa memperlebar jurang sosial antara “yang tahu” dan “yang berjuang”.
Ketiga, hilangnya kepekaan sosial. Mahasiswa yang terjebak dalam arogansi intelektual akan kesulitan memahami jeritan rakyat kecil, kehilangan empati, dan lambat laun kehilangan legitimasi moral sebagai agen perubahan.
Dan keempat, bonus demografi yang gagal. Jumlah usia produktif yang besar tidak akan bermakna jika kualitas manusianya rendah—baik dari sisi kompetensi maupun karakter. Itulah titik di mana “Indonesia Emas” berubah menjadi “Indonesia Cemas”.
Arogansi intelektual hanya bisa dijinakkan melalui kerendahan hati ilmiah (intellectual humility). Mahasiswa perlu menyadari bahwa pengetahuan bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menebar manfaat. Di sinilah pentingnya membangun budaya reflektif di kampus: setiap capaian akademik harus diikuti pertanyaan “untuk siapa dan untuk apa ilmu ini?”
Kampus juga harus berani menata ulang orientasi pendidikannya. Pendidikan tinggi tidak boleh sekadar mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk manusia yang utuh-berpikir kritis, berempati, berintegritas, dan berjiwa pengabdian. Kolaborasi antara universitas, pemerintah, industri, dan masyarakat harus diperkuat agar mahasiswa memahami langsung realitas sosial yang kelak akan mereka hadapi.
Selain itu, mahasiswa perlu aktif dalam kegiatan sosial, riset terapan, dan program pengabdian yang nyata. Dengan begitu, ilmu mereka tidak hanya tumbuh di kepala, tetapi juga hidup di hati dan tindakan.
Terakhir, penting bagi mahasiswa untuk menginternalisasi nilai spiritualitas dan kebijaksanaan sosial. Di tengah derasnya arus globalisasi dan teknologi, spiritualitas menjadi jangkar moral agar intelektualitas tidak kehilangan arah.
Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud hanya dengan banyaknya sarjana, tetapi dengan hadirnya generasi intelektual yang rendah hati, tangguh, dan peduli. Mahasiswa harus belajar menundukkan egonya, membumikan ilmunya, dan memaknai kecerdasan sebagai amanah untuk mengabdi.
Sebagaimana Bung Hatta pernah berpesan, “Pendidikan bukan untuk membuat manusia menjadi pintar, tetapi untuk membuatnya menjadi manusia.”
Maka, tugas mahasiswa hari ini adalah memastikan bahwa intelektualitas mereka bukan menjadi sumber kesombongan, melainkan sumber pencerahan bagi masyarakat. Ilmu yang dimiliki seharusnya tidak menjauhkan mereka dari realitas sosial, tetapi justru mendekatkan mereka pada persoalan rakyat, memperkuat empati, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Intelektualitas yang sejati adalah ketika kecerdasan tidak berhenti pada tataran berpikir, melainkan menjelma menjadi tindakan nyata yang membawa manfaat bagi sesama.
Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia Emas tidak akan ditentukan oleh seberapa tinggi kita berpikir, tetapi seberapa dalam kita memahami dan melayani sesama manusia. Bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan luas, tetapi oleh generasi yang mampu memaknai ilmu sebagai sarana pengabdian. Di situlah letak kemuliaan seorang intelektual sejati: rendah hati dalam berpikir, luhur dalam bertindak, dan tulus dalam mengabdi demi kejayaan bangsanya.
Oleh sebab itu, mahasiswa harus menanamkan dalam dirinya semangat belajar sepanjang hayat, semangat berbagi pengetahuan, dan keberanian untuk turun langsung menghadapi tantangan zaman. Tantangan globalisasi, revolusi digital, dan krisis moral membutuhkan generasi muda yang tidak hanya tangguh secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter. Dengan memadukan iman, ilmu, dan amal serta integritas yang membuat mahasiswa dapat menjadi pilar kokoh yang memastikan bahwa bonus demografi benar-benar menjadi berkah peradaban, bukan sekadar angka statistik yang berlalu tanpa makna.
Lebih jauh lagi, mahasiswa perlu menolak jebakan eksklusivitas akademik—pandangan bahwa kampus adalah menara gading yang terpisah dari kenyataan sosial. Justru dari kampuslah seharusnya lahir gagasan dan gerakan yang berpihak kepada kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok atau golongan sempit. Intelektualitas tanpa keberpihakan sosial hanya akan melahirkan kehampaan moral. Karena itu, mahasiswa perlu menjadikan ruang intelektualnya sebagai laboratorium sosial—tempat lahirnya solusi nyata bagi persoalan bangsa, dari kemiskinan, ketimpangan, hingga degradasi moral.
Jika mahasiswa mampu menempatkan intelektualitasnya dalam bingkai kerendahan hati dan tanggung jawab sosial, maka Indonesia tidak akan jatuh pada jurang “demografi cemas”. Sebaliknya, mereka akan menjadi motor perubahan yang menggerakkan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang beradab, berilmu, dan berkeadilan. Generasi muda hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, melainkan juga arsitek yang merancangnya. Dan arsitek sejati tidak hanya bermimpi tentang masa depan, tetapi bekerja membangunnya, batu demi batu, dengan ilmu dan pengabdian. (*)